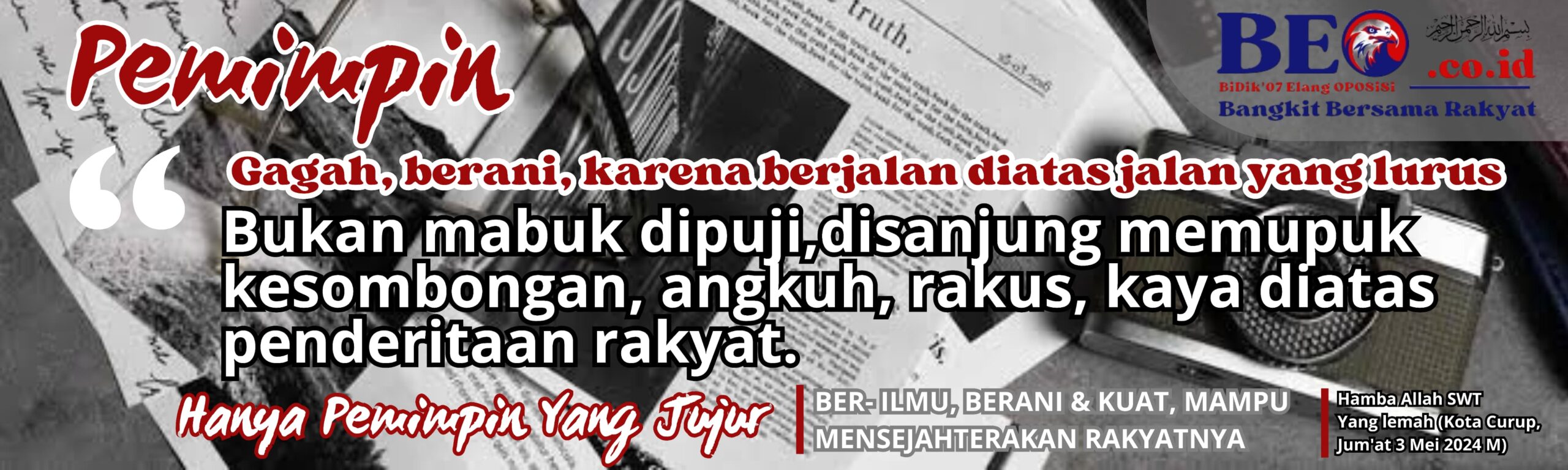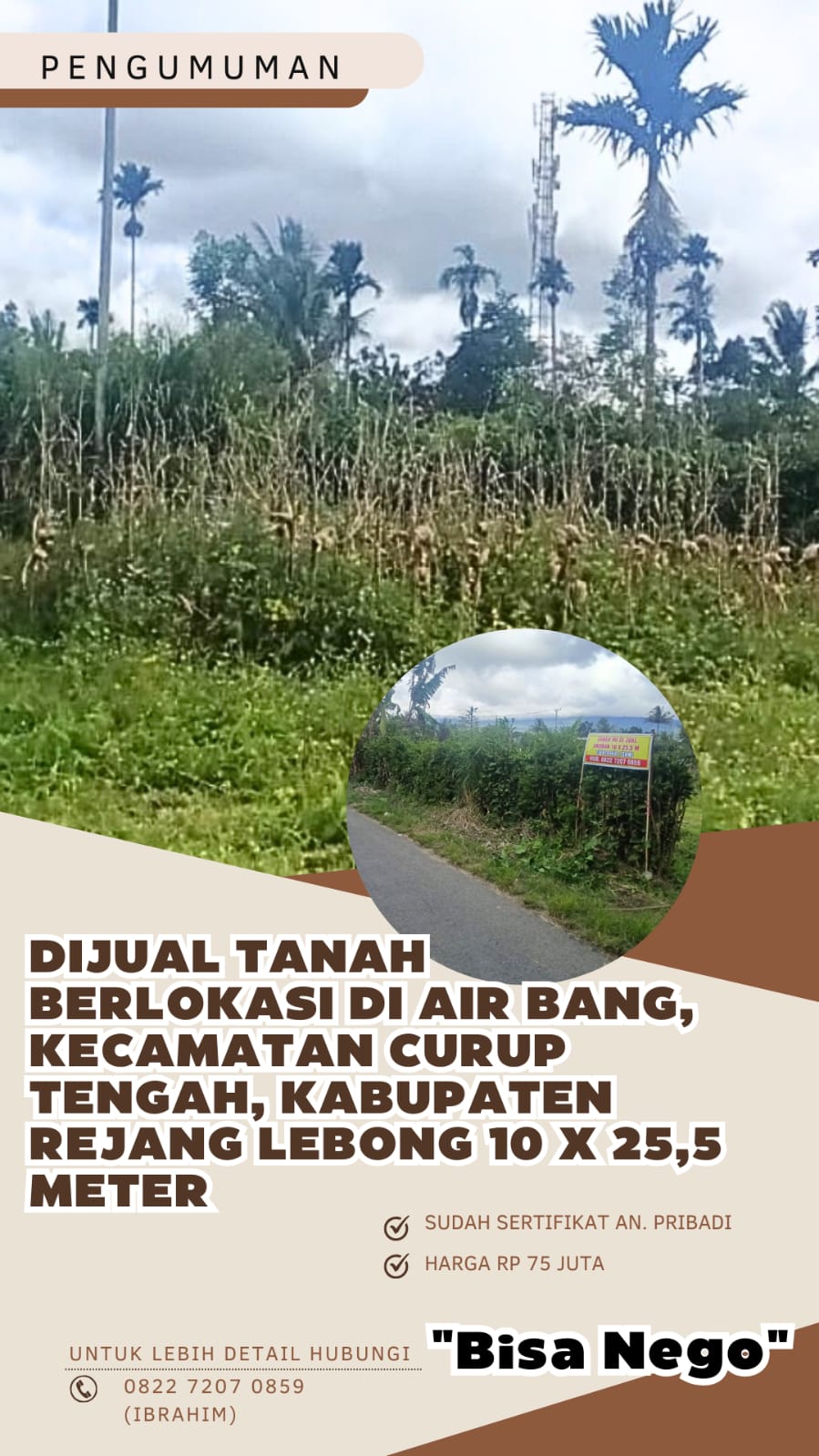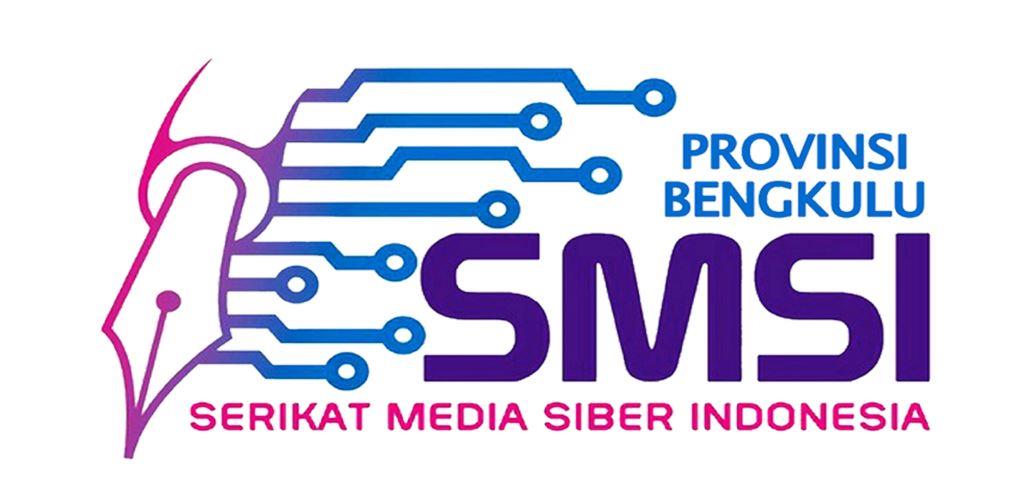Abdul Aziz, Pemerhati Sejarah
MEDAN, BEO.CO.ID – Permukaan Danau Maninjau beriak pelan memantulkan matahari pagi ke rumah beratap bergonjong empat itu.
Pantulan sinar yang menari-nari seperti ujung lilin itu masuk melalui sela kain jendela, lalu sampai ke kacamata bulat di wajah Haji Rasul yang sedang terduduk di atas bangku kayu.
Matanya terpejam. Jarinya menggulirkan biji tasbih satu persatu, mulutnya berkomat-kamit. Dia menunggu masa depannya. Dengan hampir tak sabar.
Tiba-tiba pintu kayu kamarnya berderit. Sebuah kapalo mancogok dari dalam.
“Angku masuaklah, lah lahia anak Angku. Laki-laki kata dukun melahirkan.
“Alhamdulillah ,” teriaknya serak. Wajah Haji Rasul seperti berpendar terang dan senyumnya seluas wajahnya.
Angin danau yang segar mengibas-ngibas kain jendela yang terbuka lebar.
Sinar matahari semakin menari-nari
“Insya Allah jadi penerus perjuanganku.” Bayi inilah anak laki-laki pertamanya yang hidup saat ini.
Anak pertamanya perempuan, lalu anak keduanya laki-laki, meninggal ketika berumur sehari.
Di dalam kamar, dia belai kening istrinya, Syafiah, yang berpeluh kelelahan karena mengejan.
Lalu Haji Rasul memangku bayi merah yang menangis dalam bedung kain panjang. Lamat-lamat dia lantunkan azan ke talingo anaknya.
“Sepuluh tahun, Nak, Insya Allah, ” gumam Haji Rasul.
Syarifah tersenyum mendengar gumaman itu. Sudah sering suaminya menyebut angka itu. Dia paham artinya.
“Sepuluh tahun anak kita ini akan belajar di Makkah, biar dia terbentuk menjadi orang alim seperti aku, seperti kakeknya, dan seperti kakek-kakeknya (nambo-nambonya, pen) yang terdahulu.
Haji Rasul, seorang ulama terkenal, menuntut ilmu sampai jauh ke Makkah, berguru ke Syech Ahmad Khatib al-Minangkabawi.
Sejak lama dia mempunyai rencana besar untuk anaknya. Agar jadi penerus, menjadi pewaris koleksi bukunya di Kutub Khanah, menjadi anak pembawanya ke surga.
“Saya namai wa’ang, Malik. Abdul Malik Karim Amrullah, ” katanya sambil membuai-buai bayi ini.
“Capeklah gadang, Nak.
Kawani ayah mengajar, memimpin umat ini.
Dari luar terdengar sayup-sayup hempasan lembut riak danau Maninjau yang menyentuh tapi pantai.
Berdebur pelan, seperti zikir alam.
Kalender hari itu menunjukkan 17 Februari 1908.
Sambil mendekap Malik yang merengek pelan, pikiran Haji Rasul melayang ke masa kecilnya dulu, 29 tahun silam.
Bagi Haji Rasul, niatnya kelak mengirim Malik ke Makkah ini seperti memintal ulang hikayat hidupnya sendiri.
Sama seperti ketika dia lahir pada tahun 1879 di Kampuang Kapalo Kabun, dengan nama Muhammad Rasul.
Demikian penggalan novel Buya Hamka yang ditulis dengan apik oleh Ahmad Fuadi penulis Bestseller anak rantau lahir di Bayua Maninjau, tak jauh dari kampung Hamka.
Membaca kisah hidup Hamka bagai menonton aneka film sekaligus.
Film petualangan penuh adengan mendebarkan.
Film religi yang menyentuh sanubari.
Hidupnya memang kerap berayun ekstrem dari satu kutub ke kutub lain.
Mulai dari penulis roman sampai jadi ulama besar penulis tafsir, dari gerilyawan melawan Belanda sampai dituduh makar dan ditangkap Orde Lama, dikemudian hari malah diangkat jadi pahlawan nasional.
Janji Sepuluh Tahun.
Dia duduk sendiri di atas batu besar yang layah, tempat dia biasa menatap danau ketika belajar pantun kepada Angku Muaro.
Kembali dirapalnya pantun-pantun itu, sambil melempar kerikil tak tentu ke tengah danau. Apakah dia seperti kerikil itu sekarang, tak gunanya di tepian, malah akan terbuang tenggelam dalam lautan hidup.
Pedih hatinya mengakui nasibnya sebagai bujang yang belum punya penghasilan tetap.
Anak gadis jodohnya pun direbut, dilamar orang.
Dia hibur-hibur dirinya, mungkin jodohnya bukan di Maninjau ini, tapi pada seorang gadis yang dia suka di Padang Panjang.
Inilah nasib anak muda yang diragukan dan direndahkan orang-orang kampungnya sendiri.
Semakin banyak ditulis parasaiannya, semakin bulat tekadnya untuk merantau, mencari ilmu dan peruntungan, dia ingat pantun anak Minang
Keratau madang di hulu
Babuah babungo balun
Marantau bujang dahulu
Di rumah baguno balun.
Dia terkejut. Lihatlah betapa tepatnya pantun ini menggambarkan perasaannya.
Si bujang yang di kampungnya belum berguna.
Bekerja belum diterima jodohnya pun direbut orang.
Sudah saatnya dia merantau. Harus jauh. Jauh sekali demikian tekadnya.
Dia sudah memutuskan. Kali ini dia akan pergi jauh sekali. Ke Makkah!
Ke kota yang dulu disebut-sebut ayahnya bahwa dia akan belajar di sana sepuluh tahun.
Dia tahu diri, saat ayahnya sedang kesusahan, gempa besar baru mengoyak Padang Panjang. Meluluh lantakan bangunan dan surau.
Tak mungkin meminta kepada ayahnya untuk bekal ke Makkah, aku harus bisa bisik hatinya setelah ada uangnya Si Bujang Malik datang menemui ayahnya.
“Buya, ambo ka pai marantau, ilmu ambo masih dangkal belum cukup memberi pencerahan untuk banyak orang ujar Malik.
“Kama wa’ang kini akan berjalan? “
“Kemana nasib dan kaki membawa. “
Haji Rasul menarik nafas panjang mendengar jawaban dari Malik.
“Wa’ang sekarang sudah besar, buya tak bisa menghalangi. Mendengar jawaban tersebut Malik Lega.
Awal Februari 1927, Malik berdiri di anjungan kapal milik Stoomvaart Maatschappij Nederland menatap pelabuhan Belawan yang semakin mengecil.
Anak Danau Masuk Istana
Malik melangkah masuk ke Pintu Masjidil Haram dengan nafas tertahan. Tak percaya bisa sampai ke tempat ini, berdiri di depan Ka’bah yang berselimut kiswah hitam.
Perasaannya bercampur aduk antara bahagia, syukur, dan merasa begitu kecil tak berarti.
Ketika jarinya menyentuh dinding kesat Ka’bah.
Peristiwa yang sangat menegangkan Malik dan delegasinya saat diterima oleh Amir Faisal putra mahkota yang berkuasa yang menjadi Naibul Am buat Hijaz.
Amir Faisal! Tak salah lagi.
Amir ini sendiri yang menyilahkan Malik duduk di kursi di sebelahnya. Astagfirullah. Bukan main gugupnya Malik menghadapi situasi ini.
Bayangkan, anak kampung dari tepi Danau Maninjau ini duduk bersebelahan dengan putra mahkota kerajaan Saudi, yang ditakzimi semua orang di ruang itu.
Permohonan Malik dan delegasinya
untuk mengajar Jamaah Haji Indonesia tentang cara berhaji yang benar dapat dikabulkan.
Alhamdulillah ujar mereka usai pertemuan yang sangat menyejarah itu.
Sapu Tangan dari Karimata
Malik suka berdiri di anjungan kapal Karimata melihat laut biru yang terbentang sejauh mata memandang, sampai terasa bersatu dengan birunya langit.
Ini kah lauik sati rantau batuah itu? gumamnya.
Selama di kapal ini, kebiasaan baiknya sebagai orang surau, dia amalkan.
Belum lagi waktu fajar, dia sudah terbangun, berwudhu, berdiri melantunkan azan dengan suaranya yang sahdu.
Seperti dimana pun dia berada, cepat betul dia punya kawan. Di antara seribu jemaah haji dari berbagai daerah di jawa dan Sumatera ini.
Yang menyimaknya mengaji tidak hanya orang tua, Malik beberapa kali melihat gadis sunda ikut menyimak.
Di antara mereka ada seorang yang membuat hati dan derap jantungnya melesat-lesat dari biasa.
Namanya Kulsum, gadis semampai hitam manis berumur 17 tahun.
Bayangkan, dia sampai tahu usianya.
Beberapa kali gadis ini seperti mengerling dari jauh. Kalau sudah begini, Malik harus berjuang menjaga bacaannya karena jantungnya berdebur-debur tak menentu.
Setelah dua pekan berlayar tibalah saatnya perpisahan dengan Kulsum gadis Sunda yang membuat jantung Malik berdebur.
Sehelai sapu tangan putih yang sudah disiapkan dia serahkan kepada gadis ini. “Tidak lama lagi kita berpisah, moga sampai di Makkah kita dapat bertemu lagi, kata Malik.
Kalaulah Kulsum mengerti bahasa Minang, tentu akan disampaikan sebuah pantun.
Jangan begitu adik memandang
Tajam nian sudut matamu
Terbasuh luka di hati datang
Mustahil kita dapat
bertemu
Beginilah pujangga muda kalau sedang jatuh cinta.
Menjadi Tuan Redaktur
Hamka tersenyum-senyum sendiri sepanjang perjalanan ke Medan.
Beginilah hidup dihamparkan. Di saat hidupnya terdesak, kesempatan dibukakan Tuhan.
Di Medan pula tempat tulisannya pertama kali dimuat sepulang haji, sembilan tahun lalu.
Kini ke Medan dia kembali mencari penghidupan pada Januari 1936.
Kali ini dengan sebuah tekad baru, sebagai kepala redaksi sebuah majalah mingguan.
“Mari kita perjuangkan, Pedoman Masyarakat yang masih muda ini agar mampu bersaing dengan majalah lain seperti Panji Islam, Dewan Islam, Islam Bergerak, Berita Nahdlatul Ulama, Adil, Nurul Islam dan lain-lain insya Allah kita bisa kata Malik kepada anak buahnya.
Hilang Dendam Tersisa Cinta
“Buya ini Mayjen Soeryo, ajudan Pak Harto.
Ada pesan penting Bung Karno untuk Buya. Pesannya, bila beliau wafat Buya Hamka diminta untuk jadi imam sholat jenazahnya. “
Berdetak jantung Hamka. Tidak sangka sama sekali, Saudaranya ini, Bung Karno, yang membiarkan dirinya di penjara, tiba-tiba punya sebuah permintaan khusus. Tunggu, kenapa harus ajudan Soeharto yang membawa pesan Bung Karno?
” Beliau baru saja wafat di RSPAD, semoga Buya bersedia meluluskan permintaan ini. “
Tamunya tak ingin menyinggung perasaan Hamka karena mengerti bagaimana hubungan kedua tokoh ini sejak 1950-an.
“Innalilahi wainna ilaihi rojiun. ” suara Hamka bergetar, matanya basah, berkecamuk perasaan kehilangan orang besar, orang yang dikaguminya yang sudah dianggap Saudara.
Hamka berdiri dengan sendu di depan jenazah Bung Karno.
Wajah kawan lamanya yang dulu gilang gemilang kini telah menyerah kepada ajal.
Aku maafkan engkau saudaraku bisiknya nyaris tak terdengar.
Diucapkan Takbir Allahu Akbar. Di belakangnya Presiden Soeharto, para Menteri dan pemuka masyarakat sholat di belakangnya.
Selepas sholat, mata hadirin memandang Hamka dengan hormat, beberapa berbisik dengan takzim. Orang tahu bagaimana Hamka telah menderita ditahan tanpa alasan yang jelas karena Bung Karno marah dengan kritik Hamka.
Namun kini orang yang di jebloskan ke penjara itu melepas kepergian Bung Karno dengan cinta dan lemah lembut.
Pengurus Tukang Pidato
Lama sekali Hamka menekur di depan tanah merah yang gembur.
Di kepala gundukan itu terpancang sepotong kayu bertuliskan Siti Raham binti Endah Sutan, wafat 1 Januari 1972. Di seka matanya dengan punggung tangan, dia teruskan membaca doa, mengenang kebaikan-kebaikan Siti Raham.
Ingatan Hamka melayang pada kejadian langka di Makasar.
Para hadirin mendaulat Siti Raham untuk naik podium untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, awalnya enggan setelah dibujuk, istrinya mau juga naik podium.
Suasana sejenak hening ketika mata hadirin tertuju pada Raham yang telah berdiri dengan senyum terkembang.
Hamka pun berdebar-debar menunggu apa yang akan disampaikan istrinya di depan ribuan hadirin.
“Saya diminta berpidato, padahal bapak dan ibu semua memaklumi kalau saya tidak pandai berpidato. Saya bukan tukang pidato seperti Buya Hamka. “
“Tapi pekerjaan saya adalah mengurus tukang pidato… “
“… dengan memasakkan makanan hingga menjaga kesehatannya.
Oleh karena itu, maafkan saya tidak bisa bicara lebih panjang. “
Setelah mengucap salam, Siti Raham tersenyum lalu turun dari podium.
Gemuruh suara tepuk tangan hadirin dan sebagian bahkan nengelu-elukan, Hidup Umi, hidup Umi. ” entah kenapa Hamka terharu dan matanya basah, lalu menggenggam tangan Siti Raham dengan sayang.
“Novel biografi Buya Hamka semestinya wajib kita punyai dengan membaca novel dan menonton film Buya Hamka dapat mengantarkan dan mengharu birukan emosi dan perasaan kita, baik yang membaca Novelnya,” ucapnya.
“Apalagi menonton filmnya dapat dipastikan seluruh penonton terharu dan menangis,” ujar Aziz. (Rls/Syam Hadi Purba TBK)